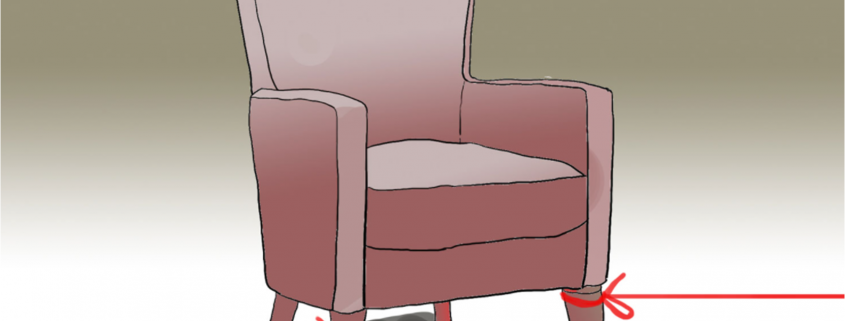Tatkala dunia dilanda pandemi Covid-19, Presiden Jokowi seperti bersua dengan ”mitos” kutukan periode kedua.
Berbagai rencana dan ambisi besarnya terhadang, upaya membangun legacy (warisan) seakan menghadapi tembok yang tinggi di depannya.Nyaris dua tahun masa kepresidenan Jokowi pada periode keduanya disibukkan dengan problem memitigasi pandemi. Enam bulan pertama masa yang berat.Survei Charta Politika dan lembaga lain, seperti SMRC dan Indikator Politik, menunjukkan merosotnya penilaian publik terhadap kinerja pemerintah secara umum meski tak serendah pada awal periode pertama. Namun, setelah itu, penilaian publik cenderung membaik walaupun belum mencapai angka approval rating sebelum pandemi Covid-19.
Di sisi lain, meski kondisi ekonomi rumah tangga ataupun nasional masih dinilai buruk, publik masih optimistis terhadap prospek perekonomian satu tahun ke depan. Dapat disimpulkan dalam kondisi pandemi, walau ada gejala peningkatan ketidakpuasan, secara umum tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Amin masih positif. Ini jelas sebuah modal politik. Pertanyaannya, apakah ini cukup memadai untuk menghadapi apa yang disebut dengan ”kutukan periode kedua”?
Meneguhkan pijakan
Periode kedua idealnya merupakan sebuah kesempatan besar. Karena tak bisa mencalonkan diri lagi, petahana tak lagi dipusingkan dengan isu bagaimana harus memenangi pemilu berikutnya. Jajaran pemerintahannya pun sudah berpengalaman sehingga lebih mudah membuat kebijakan yang tegas (Abbott dkk, 2020).
Jokowi tampaknya menyadari peluang ini. Tak heran dalam pidato kemenangannya, dia menyebutkan dirinya sudah tanpa beban. Pesan ini mengisyaratkan pada periode kedua, Jokowi akan lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan yang sangat mungkin tak populer di mata publik, tapi ia nilai sangat penting, alih-alih mengeksekusi kebijakan yang diinginkan pemilih. Tentu saja, strategi ini tidak kaku. Jokowi bak pendulum, akan berayun untuk mencegah penebalan sentimen negatif terhadap pemerintahannya.Jokowi bak pendulum, akan berayun untuk mencegah penebalan sentimen negatif terhadap pemerintahannya.
Keberanian Jokowi melawan arus tentu tak muncul seketika. Periode pertama pengalaman berharga. Bill Clinton disebut sebagai presiden yang paling mendapat manfaat pengalaman politik pada periode pertamanya dibandingkan pendahulunya (Nelson, 1998). Hal yang mirip juga terjadi pada Jokowi. Gonjang-ganjing politik dan pengalaman menjadi pemerintahan minoritas (baik di DKI maupun awal periode pertama jadi presiden) memberi banyak asupan bagi Jokowi untuk memahami konstelasi politik, pola tingkah elite politik ataupun bisnis, kebiasaan birokrasi ataupun kecenderungan perilaku pemilih.
Dalam hal ini, Jokowi sepertinya menyadari dirinya tak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Lebih dari itu, ia menyadari harus berkompromi lebih dari seharusnya. Transfer politik merupakan keniscayaan. Ini dilakukan dengan cara mengaktivasi perangkat eksekutif. Chaisty dkk (2012) memilah perangkat eksekutif ini dalam lima kategori: kekuasaan agenda politik (kekuasaan legislatif yang diberikan kepada presiden, dekrit), otoritas anggaran (kontrol terhadap belanja publik), manajemen kabinet (pendistribusian kursi menteri), kekuasaan partisan (pengaruh presiden terhadap satu atau lebih partai koalisi), dan institusi informal (kategori lain sesuai konteks tiap negara).
Namun, transfer politik saja tak cukup. Jokowi menginsyafi tak mungkin mencapai semua janji politiknya. Karena itu, ia merelakan sebagian agar kebijakan prioritasnya tetap berjalan.
Dipahami secara berbeda, bisa juga pada periode kedua ini Jokowi lebih ”memanjakan” preferensi politiknya yang berorientasi pada ekonomi dan stabilitas politik meski harus dibayar dengan persepsi kemunduran demokrasi secara umum, terutama di kalangan aktivis HAM dan demokrasi.
Manuver pertamanya yang signifikan dari pemahaman seperti itu adalah dengan melibatkan Prabowo Subianto sebagai anggota kabinetnya. Jokowi memahami sikap politiknya ini akan membuat sebagian pemilihnya uring-uringan. Ia pun memahami para pemilih Prabowo belum tentu berpaling jadi pendukung pemerintah. Namun, ini langkah politik yang diperlukan untuk memastikan tak lagi tersandera DPR seperti terjadi di paruh awal kepresidenannya pada periode pertama, sekaligus antisipasi jika partai-partai pendukung pemerintah ada yang bermanuver.
Pilihan membentuk koalisi besar sejatinya sempat dianggap spekulatif. Penilaian ini terutama becermin dari kegagalan koalisi besar yang dibangun SBY pada periode kedua kepresidenannya.Mitra-mitra koalisinya ketika itu, terutama Golkar dan PKS, justru kerap membombardir pemerintahannya. Koalisi besar yang menyokong pemerintahan Jokowi-Amin di luar dugaan justru punya disiplin koalisi relatif tinggi di parlemen. Dibuktikan dari keberhasilan meloloskan UU Cipta Kerja dan UU Harmoni Peraturan Perpajakan.
Bisa dimitigasi
Meski demikian, tiga tahun ke depan akan tetap jadi sebuah perjalanan sulit bagi Jokowi-Amin. Jokowi akan tetap menghadapi situasi atau tantangan khas pada periode kedua kepresidenan. Nelson (1998) menyebut setidaknya ada tiga faktor yang menghambat petahana bisa lebih berhasil dibandingkan periode pertamanya: warisan masalah dan atau kebijakan pada periode pertama, ketiadaan ”bulan madu” (dengan media dan publik) dan situasi lame duck government.
Berdasarkan kajiannya secara historis dalam kasus kepresidenan di AS, Crockett (2008) mengidentifikasi empat faktor: keangkuhan setelah terpilih, kepenatan personel terutama ketika sekali dihadapkan pada tuntutan pencapaian lebih baik lagi dari periode pertama, ”empty campaign”, dan juga kegagalan kepemimpinan yang antara lain juga bersumber dari sikap politik pada periode pertama. Dari konteks tiga tahun terakhir periode kedua Jokowi, tantangan terbesarnya adalah menghadapi situasi lame duck president.
Menyitir Jhonson (1986), ada berbagai situasi yang dilekatkan dengan istilah ini (lame duck president). Mulanya, istilah ini merujuk pada masa transisi ketika petahana kalah di pemilu, tapi masih tetap menjabat hingga presiden terpilih dilantik.Istilah ini juga dinisbahkan pada masa transisi ketika petahana presiden mengumumkan diri tak mencalonkan lagi untuk periode berikut atau juga tak bisa mencalonkan kembali. Belakangan, istilah ini bahkan dipakai untuk seluruh periode kedua kepresidenan Ronald Reagan.
Dalam kasus Jokowi, terminologi ini merujuk pada kondisi ketika parpol, parlemen, media, (sebagian) anggota kabinet, hingga staf pendukung kepresidenan sudah lebih sibuk dengan urusan Pilpres 2024. Ini semacam situasi ”pemilu yang kepagian”.Di satu sisi, orientasi pada pemilu berikutnya hal lumrah dan karena itu tak terelak. Namun, situasi ini akan jadi batu sandungan bagi pemerintahan Jokowi manakala bertemu tiga kondisi, yaitu koalisi pendukungnya retak atau disiplin koalisinya mengendur, anggota kabinetnya sibuk bermanuver, dan staf pendukungnya sudah siap-siap cari ”perahu” berikutnya.
Dampak ”pemilu kepagian” tak dapat ditolak, tapi bukan berarti tak bisa dimitigasi. Caranya, pertama, menata ulang dari sisi personel. Menilik tingkat kepuasan yang cenderung menurun, Jokowi bisa memainkan kartu perombakan kabinet. Meski transfer politik berupa alokasi kursi menteri harus tetap diberikan kepada partai pengusung, Jokowi perlu membangun negosiasi untuk mendapat orang-orang terbaik dari tiap-tiap partai itu. Jika diperlukan, ada tambahan transfer politik lain (seperti kepala badan) untuk mengompensasi pilihan pada figur-figur tertentu dari partai-partai itu.
Jokowi bisa mengisi posisi wakil menteri (wamen) yang saat ini banyak dikosongkan di sejumlah kementerian. Wamen-wamen ini dipersiapkan untuk mendukung kerja menteri dan juga sekaligus bersiap jika menteri itu mengundurkan diri dan atau ditarik oleh parpolnya.
Sebagai pelengkap, Jokowi perlu mempertimbangkan melakukan penyegaran di kalangan staf pendukungnya, termasuk di badan-badan ad hoc yang dibentuknya. Terutama sekali pada figur-figur yang menjadi beban dan atau yang tak lagi sepenuh hati bekerja untuk pemerintahan Jokowi karena satu dan lain alasan. Kehadiran figur baru merupakan sebuah peluang menghadirkan ide atau terobosan baru. Sebab, figur baru relatif tak terkena sindrom kelelahan politik dan atau menjadi keras kepala sebagai akumulasi pengalaman selama tujuh tahun kepresidenan Jokowi.
Jokowi juga perlu segera menyiapkan personel untuk mengisi 271 posisi kepala daerah yang akan kosong pada 2022 dan 2023 karena adanya pemberlakuan pilkada serentak di 2024. Posisi pejabat kepala daerah penting agar dekonsentrasi dan tugas perbantuan tetap terlaksana dan pelayanan publik dan pembangunan di daerah terus berjalan. Dalam hal ini, Jokowi perlu memastikan komando ada di tangannya agar tak terkesan ada dualisme loyalitas. Namun, di saat yang sama, pengisian ini perlu memperhatikan kepatutan politik agar tak terjadi resistensi terhadap para pejabat kepala daerah ini.
Kedua, Jokowi perlu menyegerakan regulasi prioritas agar selesai di 2022. Jika tidak, Jokowi akan kesulitan karena pada 2023 parlemen akan lebih sibuk ”mengurus” Pemilu 2024 atau koalisi sudah retak. Dalam situasi seperti itu, upaya meloloskan kebijakan dan regulasi akan jauh lebih sulit dan atau lebih mahal secara politik.
Selain terkait investasi dan infrastruktur yang jadi prioritasnya, Jokowi perlu mempertimbangkan untuk menyiapkan undang-undang sapu jagat (omnibus law) untuk mempercepat reformasi birokrasi. Termasuk menata ulang lembaga-lembaga tambahan negara, seperti Ombudsman, KPPU, KIP, KPU, Komnas HAM, Komisi Yudisial, dan KPK, yang saat ini bekerja terpisah-pisah. Yang tak kalah penting, menyiapkan payung hukum baru bagi para pejabat kepala daerah. Jika tidak, akan terjadi situasi menyerupai lame duck government di level daerah. Implikasinya akan banyak dan jika tak diantisipasi berpotensi jadi penghadang agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Amin.
Ketiga, memelihara modal politik. Pasalnya, situasi ”pemilu kepagian” berpotensi menggerus reputasi Jokowi. Pola pemberitaan cenderung mengadopsi pendekatan ”pacuan kuda”. Fokus media akan lebih ke arah kandidat potensial ketimbang Jokowi ataupun pemerintahannya. Terkait itu, aksi komunikasi para kandidat sangat mungkin membuat pesona Jokowi tergerus. Ini hal yang serius karena tingkat kepuasaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi selama ini antara lain juga tertopang adanya sikap partisan publik dan juga pesona individual Jokowi.
Selain memastikan kinerja ekonomi, pemerintahan Jokowi perlu menyiapkan mitigasi Covid-19 secara lebih komprehensif ketimbang sebelumnya. Meski kini sudah relatif terkendali, situasi ke depan masih samar-samar. Kemandekan percepatan vaksinasi di AS, lonjakan kasus di Singapura dan kemudian di Eropa, mengindikasikan situasi terkendali bisa dengan cepat berbalik 180 derajat.
Jika kondisi pandemi kembali memburuk dengan cepat, pemerintahan Jokowi akan menghadapi tekanan yang lebih besar apabila memilih kebijakan pembatasan sosial yang lebih ketat. Pasalnya, temuan survei Charta Politika ataupun Indikator Politik, umpamanya, menunjukkan pergeseran preferensi pemilih. Kini, dukungan terhadap kebijakan pembatasan sosial seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak lagi sekuat enam bulan di awal pandemi.
Pada saat yang sama, pemerintahan Jokowi belum menemukan resep jitu untuk mendorong pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan vaksinasi pun masih timpang antarprovinsi. Akibatnya, pemerintah juga kesulitan mendorong vaksinasi ketiga (booster) seandainya pun stok vaksin tersedia.
Dengan kata lain, pemerintahan Jokowi akan menghadapi problem lama, tapi baru: ingin cepat bergeser dari situasi pandemi ke endemi, tapi tak cukup kapasitas dan sumber daya untuk melakukannya. Situasi ini bak orang pelari cepat, tapi satu kakinya membawa beban nan berat.
Modal politik lainnya bersumber dari kemauan politik Jokowi untuk minimal mempertahankan defisit demokrasi tak terus membesar. Ini penting untuk dicermati karena permisivitas publik ada batasnya. Jika ambang batas ini dilalui, publik bisa terpicu oleh satu-dua peristiwa ketidakadilan sosial, diskriminasi, ataupun sentimen keagamaan.
Modal politik menjadi mata uang yang berharga tidak saja untuk mengarungi dinamika politik tiga tahun ke depan yang kompleks dan ambigu, tetapi juga untuk setidaknya menyamai keberhasilan pada periode pertama.
Sebagai presiden, Jokowi niscaya punya ambisi untuk dikenang keberhasilan-keberhasilannya yang monumental (legacy). Ini hal yang wajar dalam politik. Yang perlu dicermati, narasi legacy memang bisa digaungkan sejak sekarang. Namun, seiring waktu, narasi itu berpotensi dimaknai secara terbelah (diterima sebagian, ditolak sebagian) dan atau dimaknai secara berlawanan.
Punya legacy itu satu hal, tapi bagaimana hal itu dinilai merupakan hal yang berbeda. Karena itu, Jokowi seyogianya juga memperhatikan suasana kebatinan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada legacy di bidang pencapaian fisik belaka.
Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia